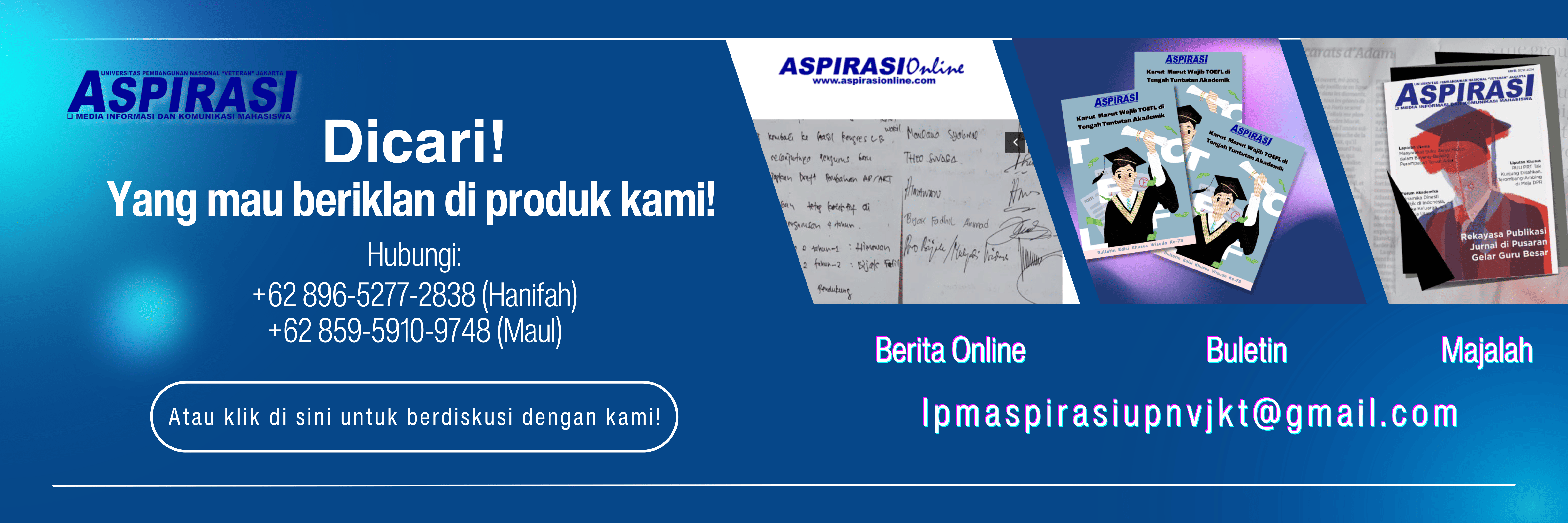Bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera pada akhir tahun 2025 menandai krisis iklim yang kian nyata. Hujan ekstrem berulang menghantam wilayah dengan kondisi lingkungan rusak akibat deforestasi. Situasi ini menunjukkan lemahnya kesiapsiagaan pemerintah.
Aspirasionline.com – Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera sepanjang akhir 2025 dipicu oleh hujan ekstrem dengan intensitas tinggi. Kondisi ini diperparah dengan lingkungan dan tata ruang yang belum optimal.
Direktorat Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kadarsah, menjelaskan bahwa pemicu terbesar banjir bandang dan longsor di Sumatera adalah curah hujan ekstrem, yakni tercatat 411 millimeter (mm) per hari.
Selain frekuensi dan intensitas hujan ekstrem yang dipengaruhi oleh perubahan iklim global, tata guna lahan juga memperbesar potensi bencana banjir dan longsor.
“Jadi setidaknya ada tiga hal utama menurut kami, yaitu satu, curah hujan yang sangat ekstrem; terjadinya siklon tropis; dan adanya faktor perubahan iklim ini,” ujar Kadarsah kepada ASPIRASI pada Rabu (24/12/25).
Kadarsah menilai kerusakan ekologis akibat deforestasi hutan Sumatera yang masif dan luas kemudian mengurangi kemampuan daerah aliran sungai dalam menyerap air. Hal ini menyebabkan air hujan langsung hanyut secara tiba-tiba.
“Berdasarkan data terbaru yang kami teliti, misalnya, kerusakan akibat degradasi dan kerusakan ekologi itu sangat menyumbang atau signifikan terhadap kerusakan yang terjadi. Jadi sekali lagi, kerusakan ekologi, deforestasi itu sangat berpengaruh dalam menyebabkan terjadinya kerusakan akibat banjir atau longsor tadi,” sambungnya.
Menurutnya, deforestasi menjadi faktor pengali terhadap dampak yang diakibatkan oleh curah hujan ekstrem.
“Yang tadinya seharusnya, andaikan misalnya curah hujan tetap terjadi, siklon tropis terjadi, siklon senyap itu ada, curah hujan 411 (mm), tetapi jika hujannya lebat dan ekologinya terpelihara, kerusakan yang diakibatkan oleh banjir dan longsor tidak akan separah seperti ini,” ujar Kadarsah.
Peringatan Berlapis di Tengah Respons yang Kurang Optimal
Terkait peringatan dini, Kadarsah mengungkapkan BMKG telah menyampaikan potensi hujan ekstrem dan anomali cuaca jauh sebelum bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.
“Delapan hari sebelum bencana kita telah memperingatkan bahwa ada siklon siniar. Nah, terus kita ulang lagi. Setelah delapan hari kita ingatkan lagi empat hari sebelumnya dan dua hari sebelumnya,” ujar Kadarsah.
Hal ini juga mencakup rekomendasi langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
“BMKG tidak hanya memberikan informasi bahwa akan terjadi curah hujan ekstrem, tetapi juga memberikan instruksi apa yang sebaiknya dilakukan. Kami berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah untuk menentukan langkah mitigasi,” tambah Kadarsah.
Meski demikian, Kadarsah menilai bahwa dalam praktiknya, tidak semua peringatan dini tersebut direspons secara optimal.
Menurutnya, informasi yang disampaikan telah diberikan dengan bahasa yang mudah dicerna. Namun, keputusan untuk pelaksanaannya kembali ke masyarakat dan pembuat kebijakan di daerah setempat.
“Jadi kita memperingatkan misalnya delapan hari sebelumnya, empat hari sebelumnya, dua hari sebelumnya. Nah, peringatan-peringatan dini itu mampu atau enggak diimplementasikan oleh pengambil kebijakan di lapangan, bahkan oleh masyarakat,” singgung Kadarsah.
Lemahnya Kesiapsiagaan menjadi Evaluasi Pemerintah Pusat
Menanggapi bencana ini, Juru Kampanye Iklim Greenpeace, Yuyun Harmono, menilai dampak bencana hidrometeorologi ini tidak hanya berhenti pada waktu kejadian, sebab pascabanjir bandang dan longsor, kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya pulih.
Yuyun menyinggung kesenjangan antara peringatan dini dan respons lapangan yang mencerminkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menjadikan mitigasi bencana sebagai prioritas kebijakan.
“Kita belum melihat keseriusan itu. Anggaran untuk BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dipotong habis-habisan dibandingkan dengan anggaran tahun lalu. Dari sisi kebijakan anggaran saja, kesiapsiagaan bencana tidak terlihat menjadi prioritas,” ujar Yuyun kepada ASPIRASI, Selasa (2/12/25).
Yuyun menilai, pemotongan anggaran yang dilakukan menunjukkan kontradiksi antara narasi pemerintah tentang kesiapsiagaan bencana dan realitas kebijakan yang dijalankan di lapangan.
Mengutip dari berita Tempo yang berjudul Banjir Sumatera: Jumlah Korban, Penjarahan, Hingga Penyaluran Bantuan, sejumlah wilayah dilaporkan mengalami terputusnya akses logistik, tersendatnya penyaluran bantuan, keterbatasan pangan dan tempat pengungsian, hingga munculnya persoalan keamanan di area terdampak yang tentu memerlukan banyak anggaran.
“Kalau kita mau mendorong masyarakat lebih sadar terhadap perubahan iklim atau bencana, seharusnya kesiapsiagaan bencana itu menjadi prioritas. Tapi kalau anggarannya dipotong jauh, kesiapan itu tidak kelihatan,” lanjutnya.
Selain persoalan anggaran, pihaknya juga menyoroti belum terintegrasinya koordinasi antar lembaga dalam merespons bencana. Fungsi BMKG sebagai pemberi peringatan dini dinilai belum diiringi dengan respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah daerah.
“Harusnya ketika early warning (peringatan awal) ada, pemerintah daerah menanggapi dengan upaya mitigasi supaya dampaknya tidak sebesar ini atau korban jiwanya tidak separah itu,” ujarnya.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah berada pada titik kritis. Yuyun menilai bahwa skala kerusakan dan jumlah korban telah melampaui kemampuan daerah untuk menangani bencana secara mandiri.
Kapasitas pemerintah daerah tentu tidak cukup. Kebutuhan yang paling mendesak, seperti pangan, pengungsian, pencarian belum terpenuhi, sehingga peran serta dari pemerintah pusat sangat diperlukan.
Yuyun menjelaskan bahwa banyaknya korban jiwa dan kerusakan akibat bencana menunjukkan lemahnya mitigasi dan respons pemerintah, sehingga dia menuntut pemerintah berhenti membiarkan ekspansi perkebunan sawit, mengurangi ketergantungan pada ekstraksi Sumber Daya Alam (SDA), serta memperkuat mitigasi bencana.
“Tentu mekanisme untuk mitigasi dan adaptasi masyarakat itu yang perlu diperkuat juga. Tentunya dengan apa? Dengan mendorong politik anggaran yang lebih besar untuk menangani sosialisasi terkait bencana, kesiapsiagaan bencana, terus kemudian juga anggaran-anggaran untuk, tanggap bencana, dan seterusnya,” pungkasnya.
Foto: Liputan 6
Reporter: Akbar | Editor : Ihfadzillah