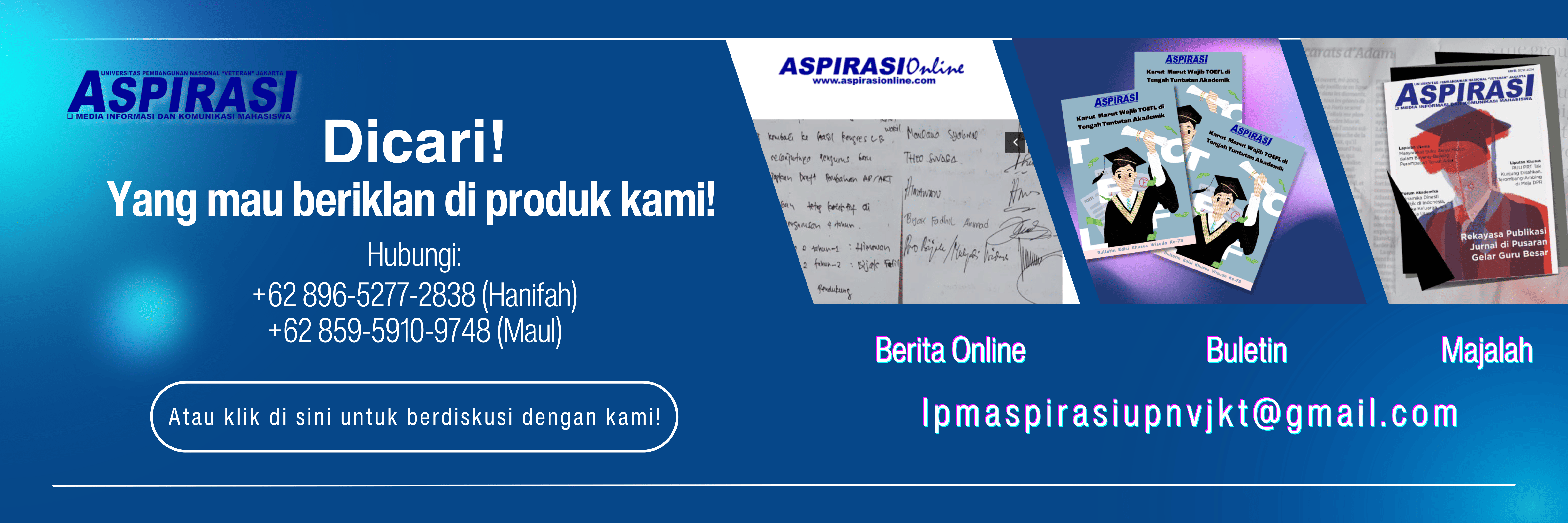Narasi ekonomi hijau kian menguat seiring meningkatnya ancaman krisis iklim. Namun di balik komitmen tersebut, Indonesia masih berada dalam bayang-bayang energi “cokelat” yang dinilai lebih murah dan praktis meski berisiko memperpanjang kerusakan lingkungan.
Aspirasionline.com – Krisis iklim tidak lagi sekedar ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang memaksa perubahan arah pembangunan nasional. Di tengah meluasnya narasi tentang transisi energi, ekonomi hijau kerap diusung sebagai jawaban atas persoalan lingkungan, sekaligus penunjang untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, di balik narasi yang megah tersebut terdapat jurang yang memisahkan dalam penerapan di negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju memiliki keunggulan dalam penerapan ekonomi hijau.
Dengan stabilitas modal dan penguasaan teknologi yang mutakhir, mereka dapat membuat teknologi yang ramah lingkungan dengan biaya yang lebih efisien, sedangkan negara berkembang seperti Indonesia harus tertatih-tatih dalam perpindahannya, dikarenakan terbatasnya modal dan tenaga ahli domestik .
Transisi energi bukan sekadar soal kemauan politik, tetapi juga soal mahalnya biaya yang sulit dijangkau negara berkembang. Laporan International Energy Agency (IEA) dalam “Strategies for Affordable and Fair Clean Energy Transitions” pada 2024 menunjukkan negara maju memiliki keunggulan stabilitas modal, sehingga mampu menarik hampir separuh investasi energi global, sementara investor cenderung menghindari wilayah berisiko.
Kesenjangan ini membuat teknologi hijau terasa murah bagi negara maju, namun menjadi beban berat bagi negara berkembang seperti Indonesia karena tingginya biaya awal (upfront cost). Tanpa fondasi ekonomi yang stabil, efisiensi ekonomi hijau pada akhirnya hanya akan menjadi angan-angan.
Jalan Terjal Transisi Hijau Indonesia
Keterbatasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam mendanai transisi hijau menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencari investor untuk mendanai transisi ekonomi hijau. Indonesia membutuhkan sekitar USD1,1 triliun (sekitar Rp18 ribu triliun) untuk mencapai transisi hijau.
Namun, jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata negara, angka ini tidak sebanding dengan kapasitas fiskal kita yang hanya mendapatkan rata-rata kita hanya sekitar Rp2,8 triliun per tahun berdasarkan data Nota Keuangan Kementerian Keuangan.
Angka kebutuhan USD1,1 triliun itu menjadi tamparan keras untuk realita fiskal kita saat ini. Dengan postur APBN yg masih terseok-seok dalam memenuhi kebutuhan lain dan utang, memaksakan transisi hijau tanpa perombakan besar-besaran adalah sebuah resiko yang sangat besar.
Namun, persoalannya bukan hanya sekedar mencari investor untuk menambal celah fiskal, melainkan dilema karena Indonesia masih mengalami ketergantungan pada bahan bakar fosil konvensional terutama batu bara dan minyak bumi.
Indonesia seakan terjebak dalam zona nyaman energi fosil. Melimpahnya cadangan batu bara dan minyak bumi dengan harga yang terjangkau membuat transisi energi terasa lambat. Bagi pemerintah, komoditas ini bukan sekadar sumber daya, melainkan tulang punggung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sulit untuk dilepaskan begitu saja demi ambisi hijau.
Berdasarkan laporan kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2024, sektor mineral dan batubara (minerba) menyumbang sekitar lebih dari Rp140 triliun per tahun dan pada sektor minyak dan gas (migas) menyumbang sekitar lebih dari Rp110 triliun per tahun. Hal ini memperkuat bahwa Indonesia masih ketergantungan dari PNBP yang dihasilkan terhadap sektor migas dan minerba, sehingga membuat tidak mudah melepasnya secara instan.
Ketergantungan ini makin terlihat jika kita melihat Pasal 16 ayat 1 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 yang masih memberikan ruang bagi batu bara dan gas dengan dalih “teknologi rendah karbon.” Hal ini menimbulkan celah legal untuk tetap menggunakan energi fosil dengan label baru.
Salah satunya ialah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Batang, proyek ini disoroti oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang dinilai sebagai transisi energi palsu sejak Oktober 2025.
WALHI menolak tegas rencana pembangunan PLTGU Batang, penolakan ini bukan hanya sekedar reaksi dari satu proyek saja melainkan bentuk perlawanan terhadap pola pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat, merusak ekosistem dan membebaskan ketergantungan pada energi fosil atas nama transisi.
Pada akhirnya, transisi ekonomi hijau jangan sampai hanya menjadi sebatas proyek tertulis di atas kertas dan menjadi tameng korporasi untuk terus mengeksploitasi alam dengan label transisi tetapi masih terus menggunakan energi fosil yang murah dan melimpah.
Kita harus jujur dan mengakui bahwa Indonesia sebenarnya belum siap secara sistemik baik dana yang dibutuhkan untuk mencapai net zero emission tidaklah sedikit, ditambah kesenjangan teknologi dan tenaga ahli yang tidak dimiliki Indonesia seperti halnya negara-negara maju.
Pengalihan dana dari energi fosil harus dilakukan untuk kita mempelajari dan meriset teknologi energi terbarukan secara mandiri. Jika kita hanya mengandalkan teknologi asing dan gagal mengelola modal negara dengan baik, maka transisi hijau hanyalah sebuah angan-angan semata yang akan menjebak fiskal negara.
Reporter: Farel, Mg | Editor: Erland
Ilustrasi: Farel